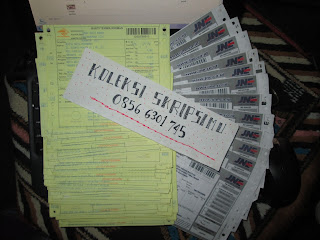Untuk melakukan hubungan diplomatik, setiap negara perlu membuka perwakilan diplomtik di negara lain. Hal ini terkait dengan hak setiap negara. Setiap negara mempunyai hak pasif (jus passivum), yaitu untuk menerima perwakilan diplomatik di negaranya. Selain itu, setiap negara mempunyai hak aktif (jus activum), yaitu hak untuk mengirimkan atau menempatkan atau membuka atau mengangkat duta untuk ditempatkan di negara lain.
Berdasarkan Konggres Wina tahun 1815 dan Konggres Aux La Chapella 1818 (Konggres Achen), perangkat diplomatik adalah:
1) Duta besar berkuasa penuh (ambassador) adalah tingkat tertinggi dalam perwakilan diplomatik yang mempunyai kekuasaan penuh dan luar biasa. Ambassador biasanya mewakili pribadi kepala negara dan bangsa serta rakyatnya.
2) Duta (gerzant) adalah wakil diplomatik yang pengangkatannya lebih rendah dari ambassador. Seorang duta dalam menyelesaikan persoalan kedua negara harus berkonsultasi dengan pemerintahannya.
3) Menteri residen, dianggap bukan wakil pribadi negara. Ia hanya mengurus urusan negara. Ia pada dasarnya tidak berhak mengadakan pertemuan dengan kepala negara tempatnya bertugas.
4) Kuasa usaha (charge de affair), kuasa usaha tidak diperbantukan kepada kepala negara. Kuasa usaha dapat dibedakan menjadi:
a. Kuasa usaha tetap yang menjabat sebagai kepala dari suatu perwakilan
b. Kuasa usaha sementara yang melaksanakan pekerjaan dari kepala perwakilan, yaitu ketika pejabat kepala perwakilan belum atau tidak ada di tempat.
5) Atase adalah pejabat pembantu dari duta besar berkuasa penuh. Atase terdiri dari dua bagian, yaitu:
a. Atase pertahanan, biasa dijabat oleh seorang perwira TNI yang diperbantukan kepada Deplu dengan pangkat perwira menengah dan ditempatkan di KBRI serta diberikan kedudukan sebagai diplomat. Tugasnya adalah memberikan nasehat di bidang militer dan pertahanan kepada duta besar berkuasa penuh.
b. Atase teknis, dijabat oleh PNS tertentu yang tidak berasal dari pejabat Deplu dan ditempatkan di KBRI untuk membantu tugas duta besar. Atase berkuasa penuh dalam pelaksanaan tugas-tugas teknis sesuai dengan tugas pokok dari departemennya. Misalnya atase perdagangan, atase pendidikan dan kebudayaan, serta atase perindustrian.
Berdasarkan Konggres Wina tahun 1815 dan Konggres Aux La Chapella 1818 (Konggres Achen), perangkat diplomatik adalah:
1) Duta besar berkuasa penuh (ambassador) adalah tingkat tertinggi dalam perwakilan diplomatik yang mempunyai kekuasaan penuh dan luar biasa. Ambassador biasanya mewakili pribadi kepala negara dan bangsa serta rakyatnya.
2) Duta (gerzant) adalah wakil diplomatik yang pengangkatannya lebih rendah dari ambassador. Seorang duta dalam menyelesaikan persoalan kedua negara harus berkonsultasi dengan pemerintahannya.
3) Menteri residen, dianggap bukan wakil pribadi negara. Ia hanya mengurus urusan negara. Ia pada dasarnya tidak berhak mengadakan pertemuan dengan kepala negara tempatnya bertugas.
4) Kuasa usaha (charge de affair), kuasa usaha tidak diperbantukan kepada kepala negara. Kuasa usaha dapat dibedakan menjadi:
a. Kuasa usaha tetap yang menjabat sebagai kepala dari suatu perwakilan
b. Kuasa usaha sementara yang melaksanakan pekerjaan dari kepala perwakilan, yaitu ketika pejabat kepala perwakilan belum atau tidak ada di tempat.
5) Atase adalah pejabat pembantu dari duta besar berkuasa penuh. Atase terdiri dari dua bagian, yaitu:
a. Atase pertahanan, biasa dijabat oleh seorang perwira TNI yang diperbantukan kepada Deplu dengan pangkat perwira menengah dan ditempatkan di KBRI serta diberikan kedudukan sebagai diplomat. Tugasnya adalah memberikan nasehat di bidang militer dan pertahanan kepada duta besar berkuasa penuh.
b. Atase teknis, dijabat oleh PNS tertentu yang tidak berasal dari pejabat Deplu dan ditempatkan di KBRI untuk membantu tugas duta besar. Atase berkuasa penuh dalam pelaksanaan tugas-tugas teknis sesuai dengan tugas pokok dari departemennya. Misalnya atase perdagangan, atase pendidikan dan kebudayaan, serta atase perindustrian.